
Kebijakan dana desa seharusnya menjadi alat utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan di masyarakat. Dengan dana desa, pemerintah memberikan pengakuan atas peran desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan. Namun, saat ini ruang pengakuan fiskal di desa semakin sempit, hanya tersisa 32%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan yang mulai membatasi penggunaan dana desa.
Salah satu kebijakan yang mengurangi ruang pengakuan adalah kewajiban mengalokasikan 30% anggaran untuk ketahanan pangan. Selain itu, batasan maksimal 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 3% untuk operasional desa juga memengaruhi kemampuan desa dalam mengelola dana. Kebijakan lainnya, seperti Kebijakan Dana Maksimal Penerima (KDMP), membatasi agunan hingga 20% dari total dana desa.
Logika dari kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Desa. Kebijakan ini berasumsi bahwa desa tidak mampu memetakan potensi dan kebutuhan mereka sendiri. Padahal, undang-undang tersebut menekankan asas rekognisi dan subsidiaritas, yang artinya desa harus diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan.
Disposisi Kebijakan
Perubahan arah kebijakan desa melalui pembatasan pengakuan fiskal dan penggunaan dana desa menjadi tantangan tersendiri. Dalam kajian implementasi kebijakan, George Edward (1980) menjelaskan bahwa disposisi menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Aspek ini mencakup pemahaman, respons, dan intensitas pelaksana kebijakan.
Adanya perubahan arah dan pembatasan akan memengaruhi pemahaman pelaksana kebijakan. Respons terhadap kebijakan, apakah setuju, mendukung, atau menolak, pasti akan berdampak pada dedikasi, loyalitas, dan motivasi kerja. Undang-Undang Desa seharusnya menciptakan disposisi yang baik, tetapi intervensi spesifik justru akan memengaruhi penerimaan pelaksana kebijakan.
Secara teoritis, disposisi terhadap kebijakan di desa akan menurun kualitasnya. Kreativitas dibatasi, sehingga apa yang dijalankan tidak muncul dari kesadaran sendiri. Ini bisa menghambat inisiatif dan inovasi di tingkat desa.
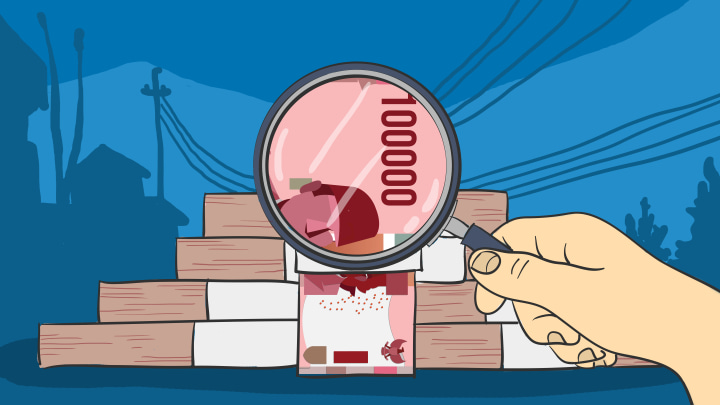
Demokratisasi desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana desa. Widya Fitriana (2024) dalam kolom opini Kompas menyatakan bahwa efektivitas penggunaan dana desa tidak dapat diukur hanya dari realisasi anggaran. Dibutuhkan perencanaan anggaran yang berbasis data, masalah riil di lapangan, skala prioritas, dan berbasis komunitas.
Sesungguhnya, kondisi ini yang seharusnya menjadi perhatian, bukan justru pemerintah mempersempit ruang pengakuan fiskal. Undang-Undang Desa juga mengamanatkan perencanaan secara demokratis, yang terwujud dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Secara tegas, desa diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, demokrasi, dan partisipasi. Pasal 54 UU No 6 Tahun 2014 mengatur bahwa hal yang bersifat strategis, seperti perencanaan desa, harus melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Namun, pertanyaannya adalah apakah prosedur tersebut cukup untuk memastikan bahwa demokratisasi desa akan bermuara pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat?

Menurut Widya Fitriana, proses deliberatif dalam demokratisasi desa harus menghasilkan masalah riil di lapangan dan data pendukung untuk menentukan arah perencanaan. Inilah titik persoalan desa, sehingga desa belum mampu melaju cepat dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Jika melihat kebijakan dalam skala nasional, misalnya Asta Cita Presiden Prabowo, poin Swasembada Pangan, dan membangun ekonomi dari desa, semangat yang dibawa masih sama. Namun, ekosistem untuk kebijakan tersebut belum mapan.
Secara imajiner, kita bisa membayangkan bahwa kebijakan itu saling menopang; ketahanan pangan di desa akan menjadi fondasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Koperasi desa juga akan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan menghubungkan dua kebijakan tersebut. Namun, dalam konteks desa, rekognisi fiskal mesti tetap dijaga, meskipun asumsi ketidakmampuan desa secara mandiri itu nyata adanya.

Persoalan yang mesti dijawab adalah demokratisasi desa yang tidak berujung pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan asumsi bahwa pelaksana kebijakan di desa tidak mampu memetakan kebutuhan di desa masing-masing. Oleh karena itu, Pasal 54 UU No 6 Tahun 2014 mesti diperdalam lagi dalam artian panduan dalam perencanaan desa.
Jika dilihat lebih dalam lagi, persoalan sebenarnya adalah tipisnya perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Meskipun proses deliberatif berjalan, yang muncul justru keinginan, sehingga tidak ada jaminan bahwa itu adalah jawaban dari kebutuhan di desa bersangkutan.

Maka dari itu, fundamental desa penting untuk didudukkan terlebih dahulu. Misalnya, apakah suatu desa fokus pada pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, atau industri. Identifikasi awal ini menjadi penting untuk selanjutnya menjawab arah perencanaan desa dan lebih spesifiknya turun pada program apa yang harus dijalankan.
Kritik Widya Fitriana sebenarnya jawaban yang mesti diadopsi menjadi sebuah kebijakan. Pertama, identifikasi awal potensi desa. Hal ini merujuk pada perencanaan berbasis data, seperti data hasil sumber daya alam yang ada di desa, data pekerjaan kebanyakan masyarakat desa, data pendapatan masyarakat, dll.
Tanpa berbasis data, pelaksana kebijakan di desa tidak akan mengenal potensi desanya sendiri, sehingga tidak memiliki arah kebijakan yang jelas. Kemudian berbasis masalah riil dan skala prioritas, hal ini juga tidak akan dapat diidentifikasi jika desa masih belum menetapkan identitas.

Jika suatu desa belum memiliki identitas jelas apakah akan fokus pada pertanian, peternakan, atau yang lain, sudah dipastikan masalah riil di lapangan dan skala prioritas tidak akan dapat ditentukan.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat, melalui Kemendes PDTT, mestinya menyiapkan fundamental desa melalui tenaga pendamping desa. Bagaimana setiap desa memang diberikan framework yang jelas agar terlebih dahulu mengenal potensi desa-nya masing-masing.
Demokratisasi desa mesti didukung dengan proses akademik yang berbasis data, sehingga bisa dipastikan proses deliberatif yang dijalankan memiliki arah yang jelas.
Penutup
Adam Smith dalam karya populernya An Inquiry into the Causes of the Wealth of Nation menyatakan, “Jika seorang negarawan mengarahkan penggunaan modal yang mereka (individu) miliki, ia mengambil kewenangan yang tidak dapat dipercayakan kepada satu orang pun.” Dalam konteks ini, jika kebijakan MBG (misalnya) akan meningkatkan demand terhadap bahan pangan, biarkan pasar yang secara organik meningkatkan produksinya sendiri untuk memenuhi demand tersebut.
Pemerintah melalui fiskalnya baik untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, tetapi pemerintah tidak perlu ikut mengintervensi proses produksi. Pemerintah tidak perlu menyeragamkan arah pembangunan di setiap desa di seluruh penjuru Indonesia. Jika memang demand itu ada, desa-desa akan bergegas dengan sendirinya untuk meningkatkan produksi dan pemerintah cukup untuk memberikan instrumen dalam mendukung pengembangannya saja.
